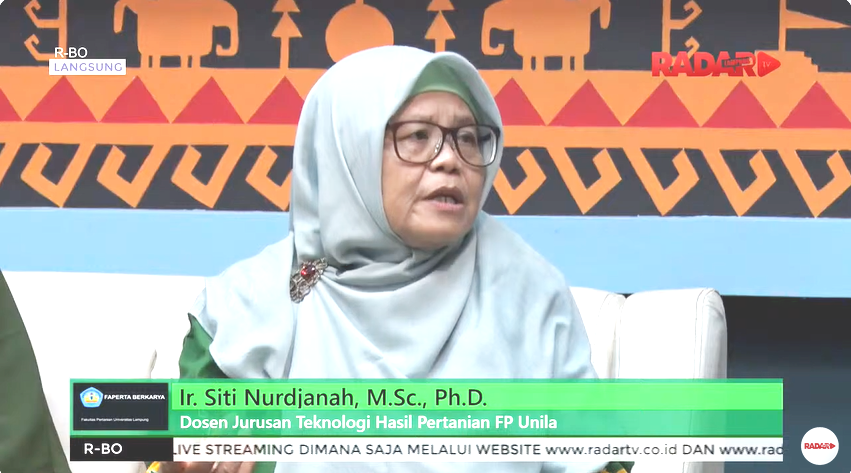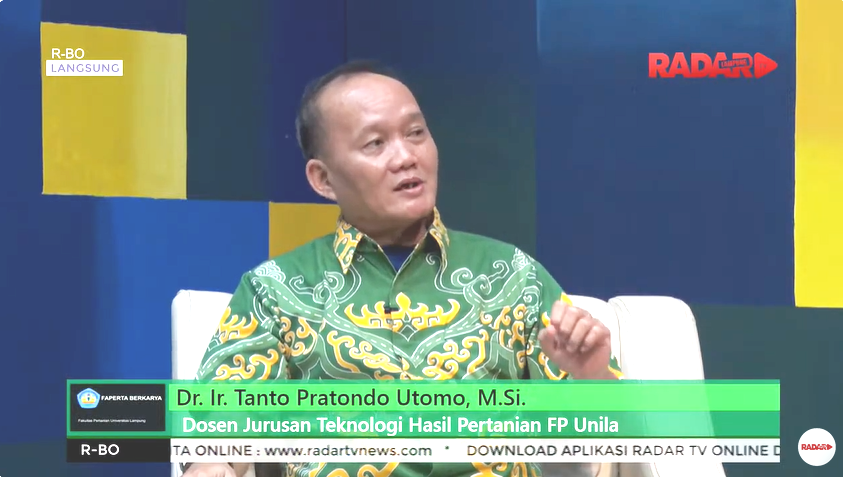Universitas Lampung (Unila) Fakultas Pertanian (FP) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP) menggelar program siaran Faperta Berkarya dengan topik Ragam Produk Berbasis Hasil Samping Kelapa Sawit, oleh narasumber Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc., Ph.D., Dr. Ir. Tanto Pratondo Utomo, M.Si., dan Diki Danar Tri Winanti, STP., M.Si., Kamis 11 Januari 2024 di Radar Lampung Televisi.
Komoditas kelapa sawit di Indonesia berkembang secara pesat dan menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.
Menurut data Statistik Perkebunan Unggulan Nasional Komoditi Kelapa Sawit tahun 2021, total luas perkebunan kelapa sawit perusahaan besar swasta (PBS) menempati posisi pertama yaitu sebesar 54,94% atau seluas 7.942.335 Ha, perkebunan rakyat menempati posisi kedua seluas 5.896.755 Ha atau 40,97%, dan perusahaan besar negara (PBN) sebesar 4,27% atau 617.501 Ha. Total luas area perkebunan kelapa sawit di Indosia sebesar 14.456.591 Ha.
Kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati yang tertinggi dibandingkan sumber minyak nabati lainnya dengan produksi secara global mencapai 75 juta ton yang pada saat ini Indonesia masih menduduki negara nomer satu di dunia sebagai penghasil sawit.
Akan tetapi, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa produk akhir sawit adalah crude palm oil (CPO) atau lebih spesifik lagi minyak goreng sedangkan masih banyak produk turunan lainnya yang memanfaatkan berbagai komponen tanaman sawit termasuk produk samping dari produksi CPO.
Sebagai gambaran, Provinsi Lampung setidaknya terdapat belasan perusahaan yang mengolah sawit menjadi CPO yang jika digabungkan menjadi satu, seluruh perusahaan tersebut, rata-rata dapat memproduksi 600 – 700 ton CPO/jam.
Padahal, dari 1 ton tandan buah segar hanya sekitar 23% yang terolah menjadi CPO dan selebihnya akan menjadi menjadi limbah yang jika tidak dimanfaatkan maka akan membutuhkan lahan penampungan yang besar dan berikutnya akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
Sekalipun sudah menjadi limbah, hasil samping produk CPO masih memiliki potensi nilai nutrisi maupun nilai tambah yang bisa dioptimalkan antara lain menjadi bahan baku feed dalam bentuk pakan lobster.
Pohon kelapa sawit, yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku CPO, mulai menghasilkan tandan buah pertama setelah berumur 3 tahun, kemudian mencapai hasil maksimum antara 12 dan 15 tahun setelah penanaman.
Akan tetapi produksi akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya umur. Pohon kelapa sawit berumur 25 tahun menjadi tidak produktif sehingga diperlukan penebangan dan penanaman kembali (re-planting). Pada tahun 2017, jumlah pohon sawit yang memerlukan re-planting paling sedikit mencapai 1,8 juta ha, kemudian meningkat menjadi 2,78 juta ha (lebih dari 40% dari total lahan perkebunan kelapa sawit.
Rata rata jumlah pohon kelapa sawit adalah 100-120 batang per hektar, dan seiap batangnya setelah dipress menghasilkan nira sekitar 45 L, maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar sebagai bahan baku gula cair, sebagaimana pohon maple yang niranya dijadikan syrup maple yang bernilai sangat tinggi selanjutnya ampas sisa perolehan nira dapat digunakan sebagai bahan baku bio-pellet dan media produksi maggot.
Pada kesempatan ini akan disajikan secara singkat tentang produk-produk yang dihasilkan berbahan baku hasil samping komoditas kelapa sawit yaitu pakan, nira sawit, bio pelet, dan media produksi maggot.
Produk Turunan Sawit untuk Pakan
Peneliti bekerjasama dengan rekan-rekan di bidang perikanan dan bermitra dengan masyarakat pembudidaya lobster di Lampung Timur dan Bandar Lampung sedang mengembangkan produk turunan sawit ke arah feed atau pakan khususnya pakan lobster air tawar.
Bahan baku yang kami gunakan adalah limbah CPO berupa bungkil inti sawit. Selain karena ketersediaannya yang melimpah di area lokal Lampung, bungkil inti sawit ini merupakan hasil samping produksi CPO yang jumlahnya mencapai 4% per ton tandan buah segar sehingga ketersediaannya cukup stabil.
Dengan memanfaatkan teknologi fermentasi dan formulasi bahan, kami berhasil merekayasa pakan pelet lobster air tawar yang biasanya berbahan baku bungkil kedelai.
Sedangkan yang kita ketahui, 100% bungkil kedelai di Indonesia adalah impor, Besaran impor bungkil kedelai ke Indonesia mencapai 5,6 juta metrik ton per tahun dan dimanfaatkan untuk pakan pabrikan sebanyak 1,5 juta ton.
Dengan formulasi pakan yang baru menggunakan bahan baku bungkil inti sawit lokal, kami dapat menggantikan bungkil kedelai hingga 34%.
Artinya, untuk membuat pakan pabrikan, jika bungkil kedelai dapat disubstitusi dengan bungkil inti sawit terfermentasi, maka kita dapat melakukan penghematan impor hingga 510 ribu ton.
Pakan yang dihasilkan sudah diuji dan sesuai dengan standar pakan lobster air tawar. Dan yang paling penting adalah pakan tersebut aman dikonsumsi oleh lobster air tawar.
Artinya, Tingkat ketahanan hidup lobster air tawar tetap baik, produktif, protein daging lobster baik, dan imunitasnya terhadap penyakit dapat terjaga karena bungkil inti sawit yang difermentasi menghasilkan probiotik untuk hewan.
Dari segi harga, pakan dengan bahan baku bungkil inti sawit ini cukup bersaing dan dapat lebih murah.
Jika pakan lobster air tawar yang premium biasa dijual dengan harga 20 ribuan per-kg maka pakan dengan formula baru ini dapat dijual dengan harga di bawah itu, minimal 15 ribu rupiah.
Dalam aplikasinya, setiap kg lobster air tawar membutuhkan pakan sekitar 3 kg dalam 1 siklus hidup atau modal pakan sekitar 45 ribu rupiah. Padahal, harga lobster air tawar untuk konsumsi perkilogramnya minimal adalah 135 ribu.
Maka margin yang dihasilkan cukup lebar sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan pembudidaya lobster air tawar.
Pemanfaatan limbah sawit akan semakin optimal jika didukung oleh berbagai pihak baik perusahaan yang menghasilkan limbah namun ingin tetap ramah lingkungan dan ekonomis, pihak pembudidaya yang dapat menghasilkan pakan mandiri, pengusaha pakan yang butuh bahan baku murah dan berkelanjutan, komponen-komponen yang bekerja pada rantai pasoknya, serta dikuatkan dengan regulasi dari pemerintah.
Dengan demikian, potensi lokal dapat menjadi raja di tanahnya sendiri tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja namun juga berbagai kebutuhan non pangan lainnya.
Potensi batang sawit tua sebagai bahan baku gula cair dalam rangka mendukung program peremajaan sawit rakyat
Batang pohon kelapa sawit yang sudah ditebang, biasanya dibiarkan atau dipotong-potong, disebar di area perkebunan di antara barisan pohon yang baru ditanam dengan tujuan agar batang batang tersebut membusuk sehingga dapat berfungsi sebagai pupuk.
Akan tetapi, hal ini tidak efektif karena pembusukan batang memerlukan waktu yang relatif lama.
Selain itu, dilaporkan bahwa kadar gula dan kelembaban yang tinggi menyebabkan batang kelapa sawit rentan terhadap serangan jamur dan serangga.
Jamur utama yang tumbuh adalah Ganoderma boninense. Pertumbuhan Jamur ini menimbulkan masalah utama dalam industri kelapa sawit karena menyebabkan infeksi pada kelapa sawit yang baru ditanam sehingga mengancam pertumbuhan dan hasil panen.
Selain itu kumbang Oryctes rhinoceros juga menimbulkan masalah yang serius, terutama pada saat peremajaan pohon kelapa sawit. Pembusukan tebangan batang kelapa sawit tua merupakan sarana yang baik untuk pembiakan oryctes.
Bagian dalam batang kelapa sawit mengandung mengandung nira sekitar 80% dari total berat batang dengan gula sebagai komponen yang dominan (11-15°Brix).
Oleh karena itu ekplorasi tentang batang tua kelapa sawit sangat penting dilakukan dalam meminimalkan limbah biomasa dan meningkatkan pendapatan petani sawit yang saat ini sebagian besar sudah memerlukan peremajaan kebun.
Gula cair merupakan produk yang sangat potensial untuk pemanfaatan batang kelapa sawit tua. Berbagai penelitian tentang metode konversi batang kelapa sawit tua menjadi gula, maupun pemanfaatan menjadi produk lebih lanjut, untuk meningkatkan nilai ekonominya telah banyak dilakukan.
Akan tetapi berbagai metode tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah potensi pencemaran linkungan akibat zat zat kimia yang digunakan, memerlukan biaya operasi dan energi yang tinggi, dan masih kurang fleksibel diterapkan ditingkat perkebunan sawit rakyat serta UMKM. Oleh karena itu kami sedang mengembangkan teknologi sederhada yang berkeunggulan untuk mengolah nira batang sawit tua menjadi gula cair yang dapat diadopsi oleh para pekebun sawit rakyat.
Potensi ampas batang sawit tua sisa produksi gula cair sebagai bahan baku bio-pelet dan media produksi maggot dalam upaya menambah pendapatan petani selama masa re-planting
Batang sawit yang telah diambil air niranya menyisakan ampas, salah satu pemanfaatan limbah ampas batang kelapa sawit yaitu sebagai bahan bakar rumah tangga atau industri adalah biomass pellets (Biopelet). Biopelet adalah jenis bahan bakar padat berbasis limbah dengan ukuran lebih kecil dari ukuran briket.
Penggunaan biopelet sendiri di Indonesia masih terbatas sedangkan sumberdaya biopelet di Indonesia sangatlah melimpah seperti limbah dari industri perkebunan.
Biopelet memiliki keseragaman ukuran, bentuk, kelembapan densitas, dan kandungan energi. Keunggulan utama pemakaian bahan bakar biopelet biomassa adalah penggunaan kembali bahan libah seperti ampas kayu yang biasanya dibuang begitu saja.
Ampas kayu yang terbuang begitu saja dapat teroksidasi dibawah kondisi yang tak terkendali akan membentuk gas metana atau gas rumah kaca.
Pelet memiliki konsistensi dan efisiensi bakar yang dapat menghasilkan emisi yang lebih rendah dari kayu. Bahan bakar pellet menghasilkan emisi bahan partikulat yang paling rendah dibandingkan jenis lainnya.
Pada umumnya biopelet digunakan sebagai bahan bakar boiler pada industri dan pemanas ruangan di musim dingin.
Selain itu, ampas batang sawit ini merupakan bahan organik kaya lignoselulosa yang masih mengandung sisa-sisa gula sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai media tumbuh larva black solider fly (Hermetia illucens L./ BSF), yang dalam perkembangannya tumbuh menjadi pupa (maggot).
Larva BSF mampu melakukan proses biokonversi menghasilkan biomassa kaya protein. Produk ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami berprotein tinggi untuk ternak unggas maupun ikan baik secara langsung ataupun setelah diolah menjadi tepung. Minyak dari larva juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti pakan ternak, subtitusi mentega, dan biodiesel.
Produksi pakan ternak dalam negeri mencapai 18,93 juta ton pada tahun 2017 dengan nilai bisnis sebesar Rp 131,20 triliun. Nilainya meningkat menjadi 19,5 juta ton dan 20,67 juta ton di tahun 2019 dan 2020. Pakan sendiri menyumbang 65,36% dari biaya produksi unggas dan Indonesia mengimpor 2,475 juta ton kedelai dan 105,8 juta USD tepung ikan sebagai bahan baku pakan tiap tahunnya.
Selain mengurangi limbah, produksi larva dan pupa BSF sebagai pakan subsitusi berpotensi menurunkan kebutuhan impor. Data lapangan dari fasilitas pemeliharaan seluas sekitar 50 m2 di Bogor dan Cimahi menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan limbah organik sebesar 7 ton/bulan dapat dihasilkan larva BSF seberat 2,5 ton/bulan dan laba sekitar Rp 9.000.000/bulan.
Sumber data, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2024.
Selengkapnya klik RAGAM PRODUK BERBASIS HASIL SAMPING KELAPA SAWIT